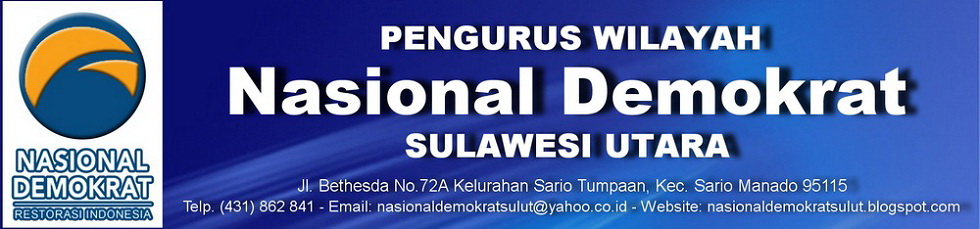Kelompok masyarakat menengah Indonesia dan kaum intelektual kritis [ khusnya yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara] acap kali menanyakan apa sejatinya makna “restorasi Indonesia”? yang dicanangkan di Jakarta, tanggal 1 Februari 2010 di bawah penamaan Nasional Demokrat. Untuk memberikan penjelasan yang memadai terhadap pertanyaan tersebut, rasanya tidak cukup hanya dengan menyodorkan buku bacaan tipis berisi manifesto, serta visi-misi Nasional Demokrat kepada kalangan tersebut sebagai penjelas.
Kendati disadari, kalau hipotesis-hipotesis yang dijadikan sebagai tiang pancang penopang gerakan, antara lain: (I) bahwa reformasi Indonesia yang telah dan sedang menghentar bangsa Indonesia menjadi negara demokrasi, justru telah merumitkan tata cara pemerintahan sehingga kesejahteraan umum menjadi sulit diwujudkan. (2) bahwa demokratisasi politik yang ada hanya menghasilkan rutinitas kekuasaan tanpa melahirkan pemimpin berkualitas dan layak diteladani. (3) bahwa demokratisasi yang tidak berorientasi kepada kepentingan publik hanya menjadi proyek reformasi tak bermakna. Dapat kami akui, hipotesis-hipotesis ini belum sepenuhnya mendeskripsikan persoalan-persoalan struktural yang dihadapi bangsa Indonesia untuk di restorasi.
Meskipun demikian, substansi persoalan: sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang dihadapi bangsa Indonesia untuk disikapi dan diartikulasikan, seperti antara lain (1) demokratisasi Indonesia harus berlangsung dinamis, dan menjadi sarana persandingan keberagaman demi untuk kesatuan, ketertiban, kompetisi, persamaan, kebebasan dan kesejahteraan. (2) demokratisasi di Indonesia harus bertumpu pada kewargaan yang kuat, dan perlu diwujudkan dengan tangan sendiri yang berkeringat untuk menggapai masa depan bangsa yang gemilang, telah dapat terformulasikan dan ditindak lanjuti melalui pintu masuk; menggalang solidaritas kesosialan, kebudayaan dan kepolitikan secara nasional. Berikut narasi argumentasi mengapa Nasional Demokrat mencanangkan gerakan Restorasi Indonesia.
II. Lemahnya sektor Negara
Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, bangsa ini terus saja terus mencari format politik bagaimana mengisi dan mengolah negara ini sesuai dengan dasar dan cita-citanya bangsa yang ideal. Visi luhur perjuangan bangsa Indonesia yang menjadi acuan kerja dan telah dirumuskan dengan ideal dalam pembukaan UUD 1945; “mewujudkan masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia” faktanya masih jauh panggang dari api. Bangsa seperti Malaysia dan Singapura yang baru beranjak membangun negara mereka dengan sumber daya alam dan jumlah penduduk yang terbatas sesudah bangsa Indonesia ini merdeka, justru kemakmuran rakyat kedua negara itu telah melampaui kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sekarang.
Negara yang diwakili oleh penyelenggara pemerintahan, dari periode-ke periode dianggap gagal memenuhi dan melaksanakan amanat penderitaan rakyat. Penyelenggara negara, dirasakan tidak lagi menjadi parts of the problem tetapi sebagai source of the problems. Penyelenggara Negara tidak mampu membangun suatu sistem penyelenggaraan negara yang baik (good governance) apalagi menciptakan persatuan dan kesatuan, memberikan keadilan, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melindungi tanah tumpah darah Indonesia. Hal ini terlihat dari tiga fase pemerintahan (Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi) dimana ketiga-tiganya gagal memenuhi panggilan tugas menegakkan keadilan dan kebenaran, melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Transformasi politik sebagai upaya pembentukan karakter bangsa yang berkepribadian terjebak dalam otoritarisme. Sementara dibidang pembangunan ekonomi, penyelenggara negara terjebak utang luar negeri dan membiarkan terjadinya sistem monopoli dan oligopoli, tumbuhnya kelompok-kelompok kepentingan (interest group) yang mencari keuntungan diri sendiri (self-interest), serta meluasnya KKN, telah menghempaskan bangsa ini ke dalam jurang anarkisme politik, keterpurukan sistem keuangan dan kemelut ekonomi yang berujung pada sengsaranya rakyat.
Begit pula denga prilaku anggota parlemen yang lebih suka bekerja untuk kepentingan kelompok partai politiknya dari pada berjuang mewujudkan aspirasi rakyat. Bahkan partai-partai politik lama, tanpa malu membatasi peran politiknya sebatas mencari keuntungan ekonomi untuk diri dan partainya. Ketidakmampuan mengartikulasikan kepentingan rakyat sebagai tanggung jawab sosial-politiknya yang utama di era reformasi, telah menghilangkan kemuliaan jabatannya, dan kepercayaan rakyat terhadap perananan negara yang melayani. Dawan Perwakilan rakyat tetap belum mampu menjadi penyeimbang kedigdayaan pejabat pemerintah. Check and Balance masih pada seputaran retorika reformasi, belum bertransformasi ke sistem demokrasi. Kenyataan ini juga menjelaskan bahwa mandat kekuasaan disalah gunakan para penyelenggara negara di legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan didapatkan dengan tujuan memperalatnya dan sebagai sarana berkonspirasi dengan kelompok-kelompok pebisnis yang dikenal dengan istilah “penguasa memberikan perlindungan kepada pengusaha dan pengusaha mebayar upeti padanya”. Wujud kolusi dan konspirasi ini terlihat dari maraknya para pejabat penyelenggara kekuasaan, penegak hukum dan para pengusaha menjadi pesakitan di pengadilan tindak pidana korupsi (KPK) karena kasus-kasus yang terkait dengan divestasi, resrukturasi ekonomi, privatisasi BUMN, aliran dana bank, proses penyusunan APBN/APBD yang merugikan dan menyengsarakan rakyat.
III. Lemahnya sistem demokrasi
Filosofi demokrasi Indonesia tertuang dalam nilai kerakyatan. Rakyat adalah pemilik kedaulatan negara.Pemerintah dan lembaga penyelenggara negara bukan negara. Ia hanya pengemban tugas rakyat. Sebagai pengemban amanat rakyat, pemerintah bertanggung jawab mewujudkan dan memelihara rasa aman masyarakat, membebaskan mereka dari rasa lapar, menciptakan kehidupan yang makmur serta menghindar dari prilaku diskriminatif terhadap sesama anak bangsa. Rumusan ideal inilah yang diamanatkan oleh UUD 1945 untuk diwujudkan.
Demokrasi kerakyatan adalah demokrasi yang mampu meningkatkan mutu kehidupan rakyat. Karena demokrasi adalah konsep yang percaya pada hukum dalam menyusun kebijakan negara. Suara publik harus didengar dan diwujudkan. Bukan sekedar ekspektasi dari common denominator. Hanya dengan mendengar dan mengikuti amanat rakyat, demokrasi menemukan bentuknya yang substantif. Bila para artikulator gagal mengeksekusi amanat dan harapan anak bangsa, gejolak politik atau tindakan revolusioner rakyat adalah bayarannya. Fakta kekinian menunjukkan, pada tingkat yang paling rendahpun prinsip kebijakan publik yang demokratis tidak sanggup diwujudkan oleh lembaga perwakilan rakyat. Kasus-kasus penggusuran rumah rakyat, terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah, gender, golongan, status social-ekonomi dan bahkan antar generasi adalah contoh-contoh kebijakan publik yang tidak demokratis yang menjadi beban sosial bangsa. Tidak mustahil, pada putaran lanjut, kondisi ini akan meledakkan kemarahan rakyat pada negara.
Semua kebijakan publik yang tidak demokratis itu bersumber dari lemahnya demokrasi kerakyatan. Pemilihan Umum yang selayaknya menjadi medan uji kualitas demokrasi, tidak pernah benar – benar ditegakkan dan dipelihara. Model indirect democracy selama ini lebih mencerminkan quasi – democracy bukan real democracy. Pemilu Indonesia memilih partai politik, bukan figur politik, baik dengan atau tanpa partai. Partai politik kemudian menunjuk orangnya untuk posisi wakil rakyat. Kondisi seperti ini, mendorong anggota legislatif selalu diperhadapkan dengan pilihan apakah mengedepankan aspirasi partai atau aspirasi rakyat. seorang aktivis politik cenderung tidak peduli pada aspirasi konstituennya demi keselamatan karir politiknya. Bila terjadi konflik antara aspirasi rakyat dan aspirasi partai, maka hampir selalu yang terakhir ini yang dimenangkan. Di era reformasi, hampir semua ketua partai yang menjabat jabatan publik tanpa ragu mengelak melakukan pilihan: mana yang diutamakan, kepentingan rakyat atau kepentingan politik.
Lemahnya penetapakn strategi pembangunan ekonomi terletak pada kesalahan orientasi pertumbuhan pendapatan yang mengabakan keadilan ekonomi. Dengan konsep ini, akumulasi kapital dimungkinkan bahkan tanpa moral keadilan. Pemerataan ekonomi melalui distribusi pendapatan, sebagai modifikasi atas kritik kebijakan ekonomi pertumbuhan, justru memperburuk moral dan prilaku ekonomi karena berorientasi pada konsep benevolent government atau kedermawanan pemerintah. Model kebijakan seperti Bantuan Likuiditas Tunai (BLT) yang disebut mendukung distribusi pendapatan telah menempatkan penduduk atau institusi pemerintahan di bawah pemerintah pusat seperti pengemis sosial. Distribusi bukan menumbuhkan budaya ekonomi produktif tetapi malah mengembangkan moral hazard yang makin meneguhkan budaya ketergantungan pada pemerintah pusat. Model pembangunan seperti ini, sejak dari masa masa Orde-Baru sampai pada kepemimpinan SBY, yang bemula dari penempatan posisi pemerintah pusat mengandalkan modal luar negeri. Akumulasi kapital luar negeri ini membuat pemerintah tidak pernah berupaya meningkatkan potensi dalam negeri.
Berganti-gantinya pemerintahan reformasi, tampak tidak mengubah strategi pembangunan yang bertumpuh pada hutang. Bila pada orde baru hutang berasal dari luar negeri di masa reformasi hutang mengandalkan obligasi dalam negeri yang jumlahnya hampir sama dengan hutang luar negeri. Strategi pembangunan yang mengutamakan hutang, tanpa perhatian pada efektifitas dan produktifitas penggunaan hutang serta peningkatan produktifitas tenaga kerja setra transfer teknologi, telah membuat perekonomian sebagai economic huble. Dipermukaan tampak baik, tetapi fundamentalnya sangat rapuh. Beban hutang negara sampai kini masih menjadi beban setiap penduduk, khususnya penduduk miskin dan berpendapatan tetap. [bagian 1. Bersambung ke bagian 2]
N.H. Eman (Ketua Nasional Demokrat Wilayah Provinsi SULUT)
Roy Erickson Mamengko ( Ketua Bid. Perencanaan, Penelitian & Pengembangan)